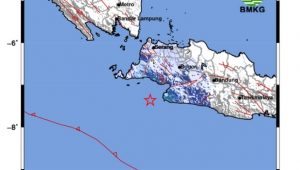SUKABUMI – Pertengahan 2003 lalu. Malam itu telah larut. Tetapi dua tiga orang masih sibuk jemarinya menari di atas papan ketik. Di meja kerja, saya, Ramli Malik-manager sirkulasi dan beberapa orang lainnya bersenda di ruang tengah.
Pekerjaan kami telah selesai, membuat minimal lima berita. Di ruangan kami bersiap menyambut kedatangan CEO Radar Bogor saat itu. Pak Hazairin Sitepu.
Tak berselang lama, sedan Toyota Altis merah marun masuk garasi. Garasi yang juga biasa menjadi gudang tumpukan reture koran harian. Saat itu Radar Bandung belum lama lahir.
Tak aneh cetak tiga ribu, reture dua ribu. Radar yang grup Jawa Pos saat itu mencari peruntungan masuk sarang maung. Karena di Bandung saat itu, koran ya Pikiran Rakyat atau Galamedia.

Radar Bandung saat awal itu berkantor di semua rumah. Bercat orange. Berpagar besi penuh karat. Catnya putih tulang. Di belakang PT Inti. Airnya kerap macet.
Seringkali saya dan beberapa kawan mandi di Pom Bensin di jalan BKR. Bahkan seringkali pula pergi liputan tak mandi dulu.
Penghuninya para generasi awal. Ada mas Obet penulis feature terbaik Radar. Kini beliau jadi penulis handal dengan nama pena Tasaro. Ada mas Heru. Lelaki Jawa sang pekerja keras. Saya wartawan baru yang dipaksa eksodus ke Bandung.
Padahal saya belum lama di Radar Bogor. Dalam fasabikunal awwalun ini ada juga wartawan berbadan besar asal Tambun Bekasi.
Didiet Aditya Rahma ini orangnya. Sama eksodus dari Bogor. Orangnya overweight. Tak aneh gampang sekali keringatan. Saat makan cara menyuapnya cepat.
Jika tengah buat berita, di mejanya penuh cemilan. Bukan hanya makanan ringan. Karena terkadang potongan ayam goreng, batagor dan siomay hadir juga disana.
Berbincang dengan pak Hazairin hingga nyaris jelang subuh. Obrolan kami banyak tema. Mulai dari bisnis koran ke depan. Hingga sukarnya menembus pasar koran Cikapundung. Karena zaman itu koran baru tak akan bisa masuk dan dijual begitu saja.
Jika sekedar masuk mungkin bisa. Tapi paling hanya diduduki tanpa dijual. Di tengah obrolan, Didiet nampak kelaparan. Diputuskanlah harus beli kudapan malam.
Didiet ajukan diri untuk berangkat. Tiga puluh menit. Satu jam. Dua jam Didiet tak jua muncul. Jelang shubuh gerbang kantor seperti ada yang mendorong. Terlihat Didiet di muka gerbang.
Bajunya kuyup keringat. Wajahnya memerah. Nafasnya terengah engah. Tapi bibirnya terkulum senyuman. “Beli martabak dimana Diet, “? tanya Pak Hazairin.
“Di Cibaduyut pak.” Seisi ruangan sontak tergelak. Karena dari kantor ke Cibaduyut lebih dari 3 km. Didiet harus berjalan kaki pulang pergi. Belum bisa naik motor saat itu. Hilang lapar pagi itu. Fragmen jelang kumandang azan shubuh itu kerap terkenang.
Beberapa saat setelah itu Didiet berjibaku aneka liputan. Mulai dari gaya hidup. Liputan ke sekolah sekolah. Hingga liputan bisnis. Tasaro selaku redaktur Didiet kerap berteriak saat melakukan editing.
Tetapi walaupun saat Didiet banyak teredit, tapi segala liputan yang diembannya selalu tuntas. Tak pernah ada keluhan. Apalagi perlawanan. Padahal saat itu, dengan badannya yang tambun Didiet harus turun naik angkot. Demi seorang narasumber.

Tak lama Didiet di Bandung. Kembali ke Bogor saya jarang sekali bertegur sapa. Baru saat kami sama sama tugas di Sukabumi, kami kembali kerap bersua. Aktivitas Didiet di Sukabumi tak hanya menjadi jurnalis. Karena Didiet juga aktif di pengajian kader sebuah partai.
Informasinya di pengajian itu pula Didiet menemukan jodohnya. Di Sukabumi pula Didiet banyak berubah. Bukan hanya wajahnya yang berjenggot. Tapi Didiet mulai rajin shalat. Bahkan sering mengingatkan jurnalis lain untuk shalat.
Sosok Didiet layak menjadi contoh jurnalis jurnalis muda. Menjadi jurnalis jangan mudah mengeluh. Kini Didiet telah selesai di dunia.
Semoga sambutan cinta dari para Malaikat menyapanya. Semoga Husnul khatimah.
Selamat jalan Dit.
(Radarbandung/izo/rs)